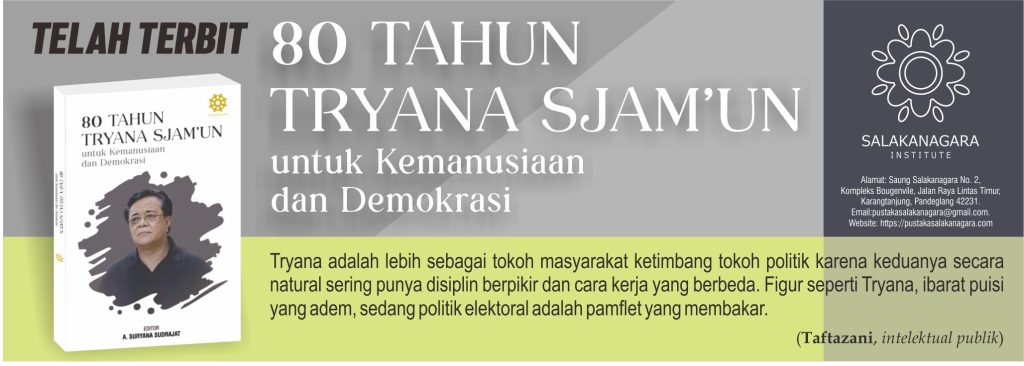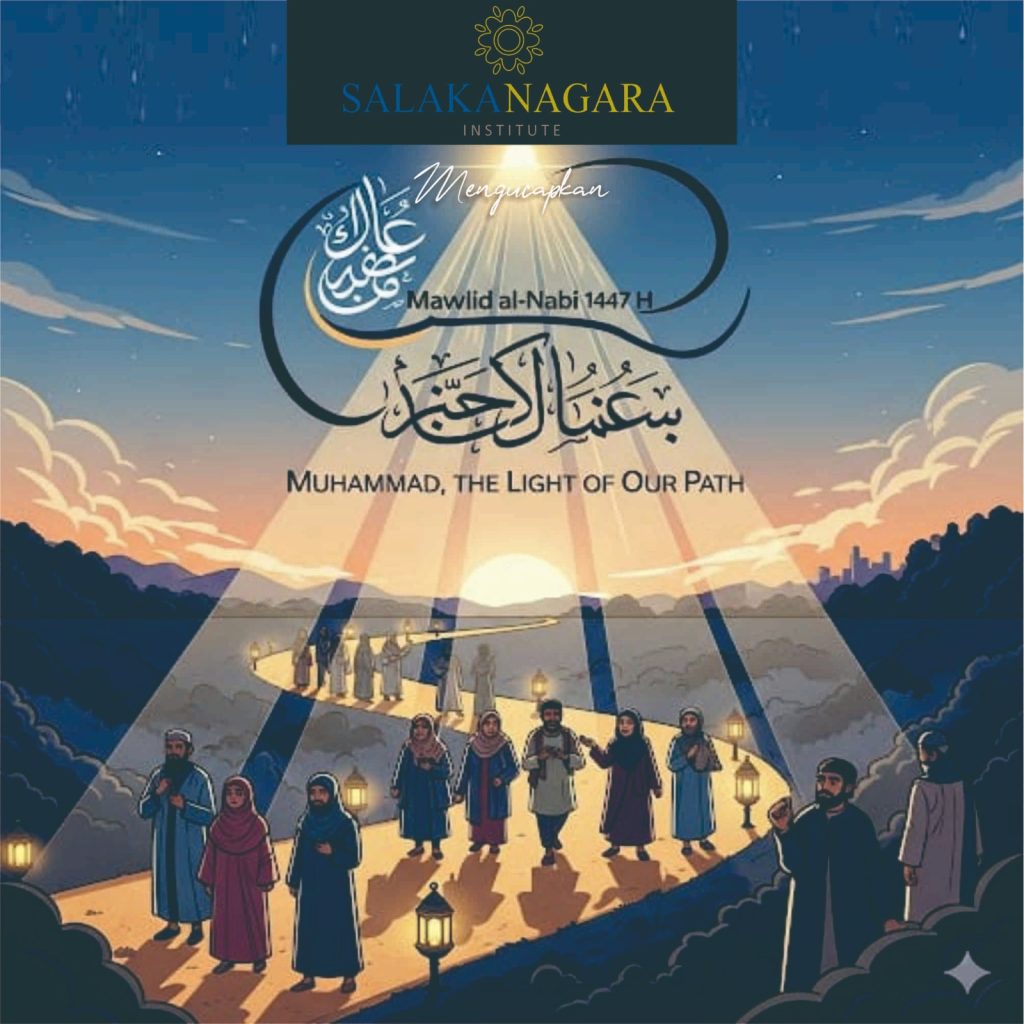Rudy Mulyono
Partai politik diseret ke tepi jurang oleh para anggota dan petingginya sendiri. Anggota legislatif berani meninggalkan kewajiban utama mereka seperti melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah, memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat, dan mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.
Dibandingkan pemilihan presiden, pemilu legislatif boleh dibilang kurang seksi. Yang ramai diberitakan cenderung yang sifatnya hiburan. Misalnya, siapa pesohor yang berhasil lolos dan yang gagal masuk Senayan. Plus riak komentar dari para elit partai, yang umumnya tidak substantif.
Tentu saja, pemilu legislatif dan posisi anggota legislatif bukannya kurang penting, apalagi jika menilik pada logika konstitusi kita; bahwa, tanpa parpol peserta pemilu, tidak akan ada presiden dan wakil presiden.
Konstitusi kita menempatkan partai politik pada kedudukan yang menentukan dalam proses pemilihan kepemimpinan nasional. Sebagaimana dalam UUD perubahan ketiga, Pasal 6A, ayat [1] dan [2], ‘rakyat [hanya] memilih [secara langsung] presiden dan wakil presiden dari calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilihan umum.’ Jika demikian, maka penyelenggaraan pemilu 2014 kali ini, sekali lagi akan menjadi ujian besar bagi partai politik peserta pemilu untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Selanjutnya, yang jagoannya menang akan memegang kekuasaan, sementara yang kalah akan menjadi “penyeimbang”-nya, dalam penyelenggaraan negara.
Selain itu, dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan, suara partai yang terakomodasi dalam wadah bernama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kemudian, akan membentuk sebuah citra pemerintahan [setidaknya] lima tahun ke depan. Dalam hal ini, tentu saja kita dapat memilahnya dalam berbagai pandangan; jangka pendek dan panjang. Yakni pemerintahan yang hanya terbatas pada periode siklus lima tahunan, dan atau merupakan sebuah pemerintahan yang terhubung dengan pemerintahan sebelumnya dan yang akan datang.
Hubungan partai politik yang berhasil mendudukkan wakilnya di DPR dan kepemimpinan nasional selanjutnya masuk dalam hubungan lembaga tinggi negara, legislatif-eksekutif, yang menentukan gerak pemerintahan ke depan. Bagaimana mengisi ruang check and balances antarlembaga tinggi negara juga menentukan ke depan. Yakni, apakah pengerahan kekuatan politik di lembaga legislatif itu akan benar menjadi energi yang memajukan penyelenggaraan negara atau justru sebaliknya. Artinya, apakah setelah mereka saling menempati jabatan-jabatan di lembaga eksekutif dan legislatif itu bisa mentransformasi spirit dari platform partainya masing-masing dengan melebur pada titik pengorbanan demi melaksanakan “janji” yang telah mereka lontarkan kepada masyarakat selama kampanye dan menunaikan amanat konstitusi negara.
Dari pengalaman dua dasawarsa terakhir, sejak masa Reformasi 1998, kerapkali partai politik diseret menuju tepi jurang oleh para anggota dan petingginya sendiri. Berbagai kasus yang membelit anggota partai, seperti korupsi dan mempermainkan hukum—sebagai dua hal yang harus diberantas dalam tuntutan reformasi di antara enam tuntutan lainnya—menjadi bukti masih memprihatinkannya kesadaran politisi sebagai wakil rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Mereka, sebagai anggota legislatif, berani meninggalkan kewajiban utamanya sebagaimana tertera dan dimengerti sejak mengucapkan sumpah jabatannya; seperti harus berupaya untuk melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah, memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat, dan mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.
Itulah yang ditengarai oleh banyak pihak bahwa, demokrasi yang berkembang hingga dekade kedua pasca Reformasi ini masih cenderung pada menguatnya demokrasi prosedural, dengan ciri-ciri bertahannya praktik money politics, bukan demokrasi yang substansial yang lebih mengusung upaya pendewasaan berpolitik (Pramono: 2013). Karena itu, layak diajukan pertanyaan, masih bisakah kita berharap pada partai politik dalam perjalanan negara ini ke depan. Sehingga, mempertimbangkan kepemimpinan nasional melalui partai politik semestinya jangan sampai menjadi sekadar adu kuat tanpa mempertimbangkan dan mengutamakan dari mana kekuatan itu berasal.
Logika Kedaulatan Rakyat
Partai-partai politik semestinya menjadikan pemilu sebagai momentum untuk memperbaiki niat dan substansi dari setiap mekanisme dan prosedur pemilihan presiden dan wakil presiden. Apalagi, realitas politik yang ada menunjukkan bahwa tidak ada partai politik yang berkuasa kecuali secara koalisi dengan partai lain.
Sebenarnya, bagi rakyat, apakah ada partai politik yang menjadi mayoritas atau dengan berkoalisi, adalah sama saja. Yaitu, apakah mereka memang punya niatan yang tulus untuk berkorban dengan bekerja keras guna menegakkan keadilan sosial dan memakmurkan rakyat. Apakah dalam melakukan deal-deal politik untuk memenangkan calon presiden [dan wapres] yang diajukan, sanubari mereka tidak dicengkeram oleh syahwat bagi-bagi kekuasaan. Logika ‘siapa punya apa dan dapat apa’ selalu akan berseberangan dengan logika kedaulatan rakyat.
Sejak awal rakyat menginginkan para politisi sudah memiliki niat dan maksud yang bersih dan memihak pada dua kepentingan dasar, yaitu keadilan sosial dan kemakmuran seluruh rakyat. Karena niat yang bersih dan tulus adalah penjaga dan benteng paling kuat bagi para politisi. Niat menjadi bahan baku dari moralitas dan etika dalam setiap usaha penyelenggaraan kewenangan publik selanjutnya. Sementara dalam hal lain yang tampak, berupa prosedur dan mekanisme politik yang sudah disepakati bersama, harus tetap dilalui secara taat asas dan hukum.
Selain itu, satu hal yang sering dilupakan dari logika kedaulatan rakyat ialah hubungan antara batin atau kesadaran dan kekuatan rakyat dengan partai-partai politik. Semestinya, setiap partai selalu ingat akan “utang”nya kepada rakyat, karena setiap dari apa yang disebutnya sebagai kekuatan partai itu pada hakikatnya adalah realitas dukungan rakyat. Bukankah sudah terbukti, jika para politisi suatu partai berkhianat pada rakyat maka ia akan ditinggalkan, sehingga ia menjadi partai lemah.
Karena itu, di tengah hubungan yang dimaksud, sesungguhnya ada ruang yang teramat penting, yakni ruang yang oleh konstitusi kita disebut dengan pencerdasan kehidupan bangsa. Dalam ruang itu ada sebuah proses di mana partai politik harus melakukan pendidikan politik secara baik, efektif dan luhur. Pendidikan politik kepada rakyat sehingga membuat mereka menyadari hak dan kewajiban sebagai warga politik dan warga sosial dalam naungan NKRI. Dengan demikian maka akan berkembanglah kehidupan demokratis secara maju dan benar. Tanpa kedewasaan dan kesadaran berpolitik masyarakat maka kehidupan demokratis tak akan pernah menyentuh hal yang substantif, kecuali sebatas prosedural belaka.
Pendidikan Politik via Media Massa
Sesungguhnya, pada era informasi kini, ada prasarana kekuatan politik lain yang punya andil besar dalam ikut serta menentukan kelangsungan kehidupan politik yang demokratis; yaitu media massa. Pemberitaan media massa yang masif sangat mempengaruhi opini dan kesadaran publik. Bahkan, dengan media, sebuah “realitas” bisa dirancang sedemikian, hingga kesadaran publik terarah kepada kecenderungan-kecenderungan tertentu. Media massa—sebagai kekuatan dan pilar demokrasi keempat—dengan demikian diharapkan mampu menempati posisi dan perannya dalam tugas pencerdasan politik masyarakat.
Dalam konteks realitas Indonesia sekarang—di mana batas-baur kepentingan pemberitaan, nilai ekonomi, kepemilikan media massa dan kepentingan politik, hasrat berkuasa dan moralitas pengabdian bangsa sudah sangat sulit dijernihkan—maka menjadi tidak mudah bagi sebuah media untuk kembali pada khittah-nya, sebagai pilar demokrasi, memberikan pencerdasan politik. Persoalannya, apakah media massa bisa lepas dari bias kepentingan dan terseret pada kepentingan politik seseorang atau partai. Media massa yang bermental partisan tidak akan bisa menjadi pilar demokrasi yang mencerdaskan bangsa.
Secara praktik politik, wilayah perhubungan mereka pun kontras terlihat dalam lingkup, yang boleh kita katakan sebagai zona terbuka dan tertutup. Zona yang terbuka meliputi berbagai hal dari diseminasi visi-misi dan program hingga urusan pencitraan; dan zona yang tertutup dan terbatas, yang biasanya terkait dengan ‘siapa punya apa dan dapat apa’. ***