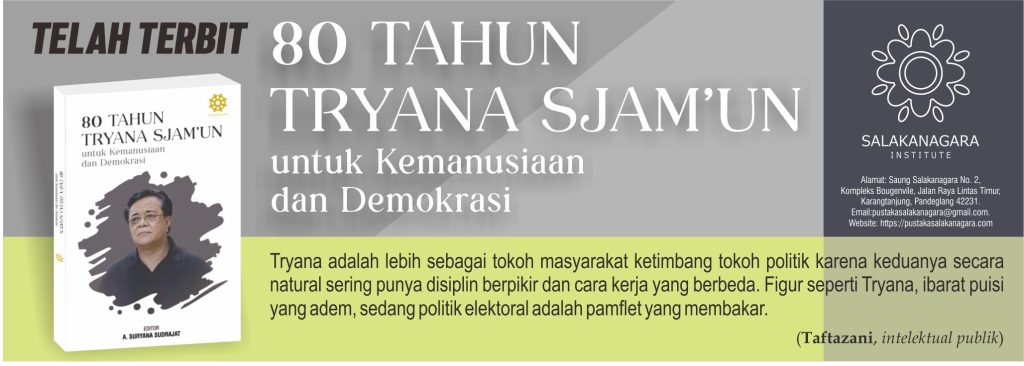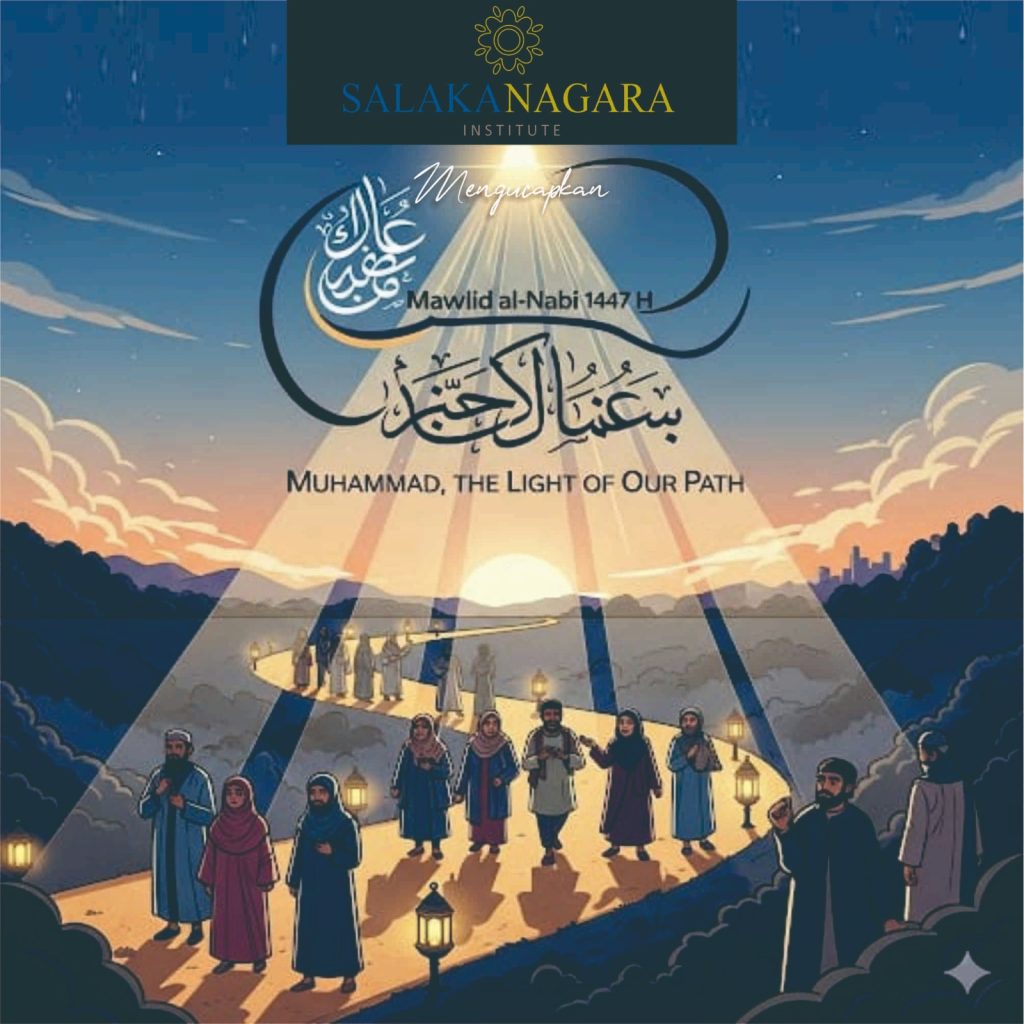Masa depan sebuah bangsa dan negara ditentukan oleh sekuat apa tekad dan peran masyarakat dalam ikut serta mengisi kemerdekaan yang dimilikinya. Ragam pilihan aktivisme kemanusiaan di berbagai bidang saling berinteraksi satu sama lain, membentuk sketsa sebuah bangsa. Adalah sebuah fitrah, bahwa setiap individu atau kelompok mesti menentukan sendiri goresan apa yang hendak ia torehkan pada wajah bangsanya.
Setelah melampaui dua dekade Reformasi ‘98, kita perlu meninjau kembali perjalanan bangsa dan bernegara ini. Benarkah seperti kata sebagian orang bahwa nilai-nilai kemanusiaan kita yang belas-kasih pada semesta—dalam bentuk harmoni, keadaban dan kesantunan—sudah tergerus ketamakan akan tahta dan harta, sehingga menjauhkan kita dari mimpi baldatun toyyibatun wa Rabbun Ghafur?
Benarkah pilihan akan demokrasi—yang kita anggap sebagai jalan lebih cepat mencapai cita-cita kebangsaan—kerap ditelikung oleh kepentingan sesaat akan kekuasaan dan jabatan, sehingga abaikan tugas pencerdasan bangsa dan peningkatan kesejahteraan rakyat?
Jika melihat kondisi rakyat pada umumnya—dengan potensi negeri yang mengiri hati bangsa lain ini—seolah jawab atas pertanyaan hipotetis di atas “benar”. Andai dilokalisir pertanyaan itu pada provinsi Banten—sebagai case study-nya; beberapa riset dan laporan malah menguatkan jawaban itu.
Tentu bukan karena keliru memilih demokrasi jika realitas sosial memprihatinkan, namun sikap dan laku kita dalam berdemokrasi-lah yang jadi soal. Jika demokrasi yang dilakukan hanya berpedoman pada prosedur belaka tanpa menunaikan substansi atau rohnya, maka ia akan mengikuti pragmatisme dan kepentingan kelompok tertentu yang punya kuasa dan biaya. Demokrasi yang berjalan lepas dari kendali akhlak dan etika akan abai pula terhadap keberpihakan pada rakyat, yang semestinya menjadi jiwa setiap kebijakan. Jika begitu, nilai kemanusiaan dan rasa keadilan pun ditinggalkan. Dan selanjutnya, rakyat bisa kehilangan kepercayaan.
Menilik berbagai praktik pemerintahan kini, kadang terasa sulit menemukan mana yang dilakukan untuk kemaslahatan rakyat secara utuh. Problem di masyarakat pun kerapkali memunculkan dilema dalam penyelesaiannya. Lalu, berdiam, cuek, atau berputus-asakah kita? Tentu tidak. Karena masalahnya bukan pada kuatnya hegemoni kaum pelanggar atau penindas, tetapi terletak pada diamnya kita (rakyat) dari aktivitas untuk memperbaiki keadaan.
Karena itu, setiap noktah upaya konstruktif menjadi penting. Memang, tidak akan serta merta bisa mengubah kondisi dalam sekejap. Namun, setiap anak bangsa diberi hak moral sekaligus tanggung jawab untuk melakukan pembenahan. Hak dan tanggung jawab itu sejatinya adalah panggilan Ibu Pertiwi yang tak pantas disia-siakan. Kewajiban kita ialah menunaikan; dan hasil, biarlah “sang waktu” yang menarasikannya. Kehadiran Salakanagara Institute adalah sebuah ikhtiar untuk memenuhi panggilan itu. (rm)